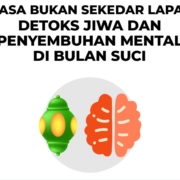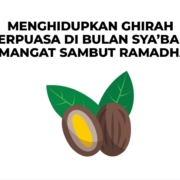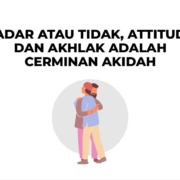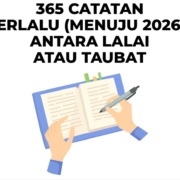Puasa Bukan Sekedar Lapar: Detoks Jiwa dan Penyembuhan Mental di Bulan Suci
Puasa Bukan Sekedar Lapar:
Detoks Jiwa dan Penyembuhan Mental di Bulan Suci
Adelia Kusuma Wardhani, S.H., M.Kn.*
Memasuki Quarter Life Crisis
Saat ini kita sering mendengar ungkapan dari generasi Gen Z “sedang di fase quarter life crisis nih….”. Lalu, apa sebenarnya quarter life crisis? Istilah ini merujuk pada krisis emosional dalam bentuk stress, depresi merasa diisolasi dan ketakutan akan masa depan dan dapat terjadi pada individu usia antara 18-30 tahun.[1] Kondisi ini sangat berkaitan dengan kesehatan mental seseorang.
Dalam pandangan Islam, kesehatan mental memberikan dampak baik pada kehidupan individunya dengan melakukan hal-hal yang berguna bagi umat manusia.[2] Kesehatan mental tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan gangguan, tetapi sebagai kondisi hati yang tenang, kokoh, dan terarah kepada Allah ﷻ. Allah ﷻ berfirman:
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَىِٕنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِۗ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَىِٕنُّ الْقُلُوْبُۗ
“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, bahwa dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram.” (QS Ar-Ra’d [13]: 28).
Ayat ini menegaskan bahwa ketenteraman hati sejatinya bersumber dari dzikrullâh. Orang yang beriman dan senantiasa mengingat Allah ﷻ akan merasakan ketenangan batin, tidak mudah gelisah, cemas, atau larut dalam ketakutan terhadap masa depan.
Dengan demikian, salah satu jalan menghadapi quarter life crisis adalah memperkuat iman dan memperbanyak mengingat Allah ﷻ. Ketika hati terhubung dengan-Nya, kegelisahan akan berkurang dan harapan akan tumbuh.
Quarter life crisis cenderung lebih ringan pada individu yang memiliki kesehatan mental yang positif.[3] Dalam konteks ini, bulan Ramadhan yang penuh keberkahan menjadi momentum istimewa. Ibadah puasa, dzikir, tilawah Al-Qur’an, dan qiyam Ramadhan merupakan sarana efektif untuk membersihkan hati, menata kembali tujuan hidup, serta menumbuhkan ketenangan jiwa. Dengan demikian, Ramadhan bukan hanya melatih fisik, tetapi juga menyehatkan mental dan menguatkan ruhani.
Puasa sebagai Detoks Jiwa
Puasa merupakan salah satu ibadah pokok dalam ajaran Islam yang memiliki kedudukan sangat penting. Secara terminologis, puasa didefinisikan sebagai menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai dengan terbenam matahari dengan disertai niat dan memenuhi syarat-syarat tertentu.[4]
Kewajiban puasa telah ditegaskan oleh Allah ﷻ dalam firman-Nya pada surah Al-Baqarah ayat 183. Allah ﷻ berfirman:
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَۙ
“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (QS Al Baqarah [2]: 183).
Ayat ini memberikan makna puasa yang bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga pengendalian dorongan batin. Puasa juga menjadi jembatan relasi antara ibadah fisik dan kesehatan psikologis.
Definisi nafsu saat berpuasa tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga atas perbuatan maksiat yang dapat menjauhkan diri dari Allah ﷻ. Seperti halnya menjaga lidah dari perkataan tercela seperti kebohongan, ghibah, fitnah ataupun hal lain yang dapat melukai perasaan orang lain yang memicu perpecahan atau perdebatan. Maka dari itu, menjaga hawa nafsu dimaksud juga menjaga lisan dan pandangan agar tidak memicu adanya maksiat saat berpuasa.
Puasa juga menjadi ruang latihan mengelola amarah, impulsivitas, dan kecenderungan konsumtif yang sering menjadi pemicu gangguan mental. Melalui pengendalian keinginan dan emosi, secara tidak langsung hal ini meningkatkan kecerdasan emosional. Dengan menahan rasa lapar, haus serta menghindari perilaku negatif, seseorang belajar untuk lebih sabar dan berpikir sebelum bertindak.[5]
Puasa sebagai Terapi Mental
Dengan segala keutamaan puasa tersebut, maka puasa dapat menjadi jalan untuk melakukan terapi kesehatan mental seseorang. Puasa selama Ramadhan dapat memperkuat mekanisme dalam menghadapi stress dan meningkatkan ketahanan psikologis. Puasa juga dipercaya meningkatkan rasa syukur, makna hidup, dan kepuasan diri selama menjalani puasa. Pengalaman emosional seringkali dikaitkan dengan aspek spiritual Ramadhan yang mendorong refleksi diri dan tanggung jawab sosial.[6]
Pengendalian diri selama berpuasa dapat menjadi kunci dalam meredakan kecemasan yang muncul akibat quarter life crisis. Latihan menahan diri dari keinginan dan dorongan sesaat melatih seseorang untuk lebih sabar, tenang, dan tidak reaktif terhadap tekanan hidup.
Terapi mental melalui puasa juga terbentuk dari perubahan pola hidup yang lebih terstruktur selama Ramadhan. Aktivitas ibadah seperti shalat malam, tilawah Al-Qur’an, dan dzikir menghadirkan ritme spiritual yang teratur. Ritme ini menumbuhkan kesadaran diri (self-awareness) sekaligus kesadaran akan kehadiran Allah ﷻ, sehingga hati menjadi lebih terarah, stabil, dan penuh makna.
Pada akhirnya, puasa Ramadhan mengajarkan bahwa kesehatan mental tidak harus selalu dimulai dari teknik psikologis yang rumit, tetapi dapat tumbuh dari latihan spiritual yang sederhana: berhenti sejenak, menahan diri, dan kembali menyadari tujuan hidup. Ketika seseorang mampu menahan dirinya dari sesuatu yang halal demi ketaatan kepada Allah ﷻ, maka sesungguhnya ia sedang membangun kekuatan batin yang kokoh sebagai fondasi kesehatan mentalnya.
* Dosen Fakultas Hukum UII.
Maraji’ :
[1] Inka Sukma Melati. “Quarter Life Crisis: Apa penyebab dan solusinya dilihat dari Perspektif Psikologi?”. Inner: Journal of Psychological Research.Vol 4. No. 1. 2024.
[2] M. Azmi Ubaidillah, Edi Hermanto, M. Nahdan Syabil, M. Rapi. “Puasa dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sains”. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Vol 2. No 1. 2026.
[3] Inka Sukma Melati. “Quarter Life Crisis.
[4] M. Azmi Ubaidillah, Edi Hermanto, M. Nahdan Syabil, M. Rapi. “Puasa.
[5] Dwi Larasati. “Kesehatan Di Bulan Ramadhan: Pengaruh Puasa terhadap Kesehatan Fisik dan Mental”. Jurnal Dinamika Sosial dan Sains. Vol 2. No 2. 2025.
[6] Andik Isdianto, Nuruddin Al Indunissy, Novariza Fitrianti. “Dampak Psikospiritual Puasa Ramadan Terhadap Stress, Kecemasan dan Ketahanan Mental”. Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS). Vol 1. No 1. 2025.